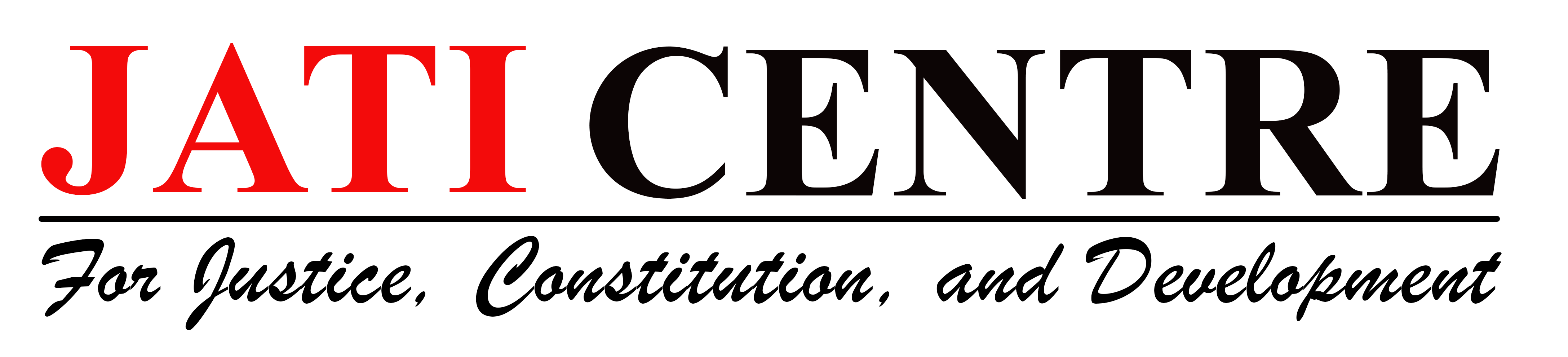Merenungi Ajaran Bapak Para Nabi Mengasah Hati di Tengah Pandemi

Pagi ini, ketika dalam perjalanan menuju kantor sembari mendengarkan Radio di Chanel Voice Of America (VoA), terdengar hal yang menarik dalam pemberitaan mengenai Negara Prancis. informasinya bahwa Negara Prancis menghentikan serta menghapuskan aturan mengenai pembunuhan ayam jantan pada peternakan dinegaranya yang selama ini ayam jantan dari sisi tubuh, dan tingkat produktifitas dianggap tidak sebanding dengan Ayam betina yang dapat bertelur dan menghasilkan daging, tentu saja aksi ini dipelopori oleh organisasi kesejahteraan hewan di negara tersebut.
Hal di atas sangat mengusik dan membuat jiwa kemanusiaan ini berontak, karena dibagian negara lain betapa pedulinya dengan kesejahteraan hewan jika dibandingkan dengan kepedulian kita pada kemanusiaan, di negara kita yang seakan akan telah terkikis kepedulian pada sesama. Menengok kembali melihat wajah negeri tercinta yang saat ini mendapati ujian begitu dahsyat dengan meningkatnya Covid 19 membuat Ibu pertiwi tidak berhenti meneteskan air mata.
Merujuk pemberitaan dari Kompas.com, pemerintah resmi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali, penerapan kebijakan ini berkaitan dengan masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan ini secara tegas diumumkan oleh Presiden Jokowi setelah mendapat masukan dari sejumlah pihak antara lain, Para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memang berkembang sangat cepat, terutama adanya variant of concerns atau varian baru virus corona. Di kota Palu pun diberlakukan pembatasan aktivitas dengan membatasi pusat perbelanjaan, menutup seluruh akses dan tempat berkumpulnya warga Kota Palu hingga Pukul 21.00 WITA.
Kebijakan pemerintah pusat dan derah terkait PPKM tentu menimbulkan riak-riak di masyarakat, karena belum pulih perekonomian mereka setelah penerapan PSBB tahun lalu, kini mulai lagi dengan menahan diri untuk tidak beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan ini berdampak pada supir taksi, angkot, ojol, pengamen, dan pemulung, Dengan pendapatan yang menurun drastis.
Berbagai problematika yang melanda bangsa ini, tentu sudah seharusnya kita untuk memulai inisiatif saling bahu membahu dan membantu, sebab pemerintah memang mempunyai kelengkapan Instrumen, baik itu sistem maupun alat negara. Namun jika mengharapkan hal itu tentu akan menyita waktu, mengingat pemerintah juga taat pada prosedur administrasi birokrasi yang begitu panjang, di tengah kebutuhan yang tidak dapat menunggu lama, maka siapa lagi kalau bukan kitalah yang bergerak untuk itu. Indonesia bukan negara Agama namun warga negara Indonesia sudah pasti beragama maka sudah saatnya kita kembali pada nilai-nilai ajaran kemanusiaan dalam agama guna bersama menghadapi pendemi yang kini merebak.
Nabi Ibrahim selaku Bapak Para Nabi yang juga merupakan Bapak dari agama-agama Samawi telah mengajarkan sebuah hikmah yang dapat diambil pelajaran serta keteladanannya. Dimana beliau mengalami pergolakan batiniah antara mengikuti perintah Allah atau tetap pada kepentingan pribadinya yang mengutamakan keluarga dalam hal ini anak satu-satunya yaitu Ismail, Pada malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi. Nabi Ibrahim merenung panjang, “Haruskah ia mengikuti perintah Tuhannya untuk melepaskan hal yang paling ia sayangi, hal yang paling ia sukai? Apakah mimpi ini benar dari Allah atau bukan?” Kegalauan Nabi Ibrahim ‘alaihissalam mendapatkan jawabannya pada malam hari berikutnya, yakni pada malam hari 9 Dzulhijjah, bahwa ia benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya yang bernama Isma‘il. Kisah tersebut kemudian diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran:
Artinyan :
“Ketika anak itu memasuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa bepergian dan berjalan, Nabi Ibrahim ‘alaihissalam berkata kepada anaknya: Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu? Isma‘il anak Ibrahim menjawab: Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintah (Allah) kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar” (QS Ash-Shâffât 102).
Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membangun harmoni dengan sesama. Sebab, Islam diturunkan dengan sempurna dalam mengatur tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Sejatinya, bukan hanya keharmonisan dengan manusia (hamblun minannas), akan tetapi dilandasi harmoni dengan Allah SWT (hablun minallah) yang berbuah kemesraan terhadap lingkungan alam (hablum minal ‘alam). Ketiganya merupakan kesatuan yang tak bisa dipisahkan dan mesti dijaga keseimbangannya. (QS 3: 112).
Nabi Ibrahim mengajarkan pertama, beriman atau beragama pada dasarnya melawan hawa nafsu atau kesenangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung mengikuti keinginan nafsunya, yakni ingin melakukan hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan yang lainnya tanpa mempedulikan hal tersebut menyakiti, merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain atau tidak. Di sinilah agama hadir memberikan seperangkat aturan, yakni mengatur perbuatan ini haram dan perbuatan itu halal, tindakan ini boleh dan tindakan itu tidak boleh, hal ini baik dan hal itu buruk, dan seterusnya. Dengan demikian masing-masing dari orang yang beragama seharusnya mematuhi aturan agama, bukan mengikuti kesenangan atau kehendak nafsunya.
Dalam kisah Nabi Ibrahim, kenikmatan tertinggi disimbolkan dengan memiliki anak, tapi Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan hawa nafsu kecintaan kepada putranya dengan mengikuti perintah Allah subhanahu wata’ala. Pelajaran atau ‘ibrah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam di atas yaitu penegasan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dalam hal ini hak hidup. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim ‘alaihissalam untuk menyembelih putranya bertujuan untuk menguji keimanannya atau ibtilâ` (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ), sehingga ketika beliau tulus hendak menunaikannya, Allah subhanahu wata’ala mengganti objek sesembelihannya dengan binatang. Penggantian “objek kurban” dari manusia ke binatang mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup yang seorang pun atas nama apa saja tidak boleh menghilangkannya.
Pelajaran yang penuh dengan Makna Spiritualitas yang dijalani oleh Nabi Ibrahim AS dapat diterjemahkan dimasa kini adalah dengan mengenyampingkan keinginan dirinya dengan mengikuti Perintah Allah SWT, dimasa Covid saat ini seluruh komponen masyarakat mengalami kesusahan namun saat kita sudah dan masih mau berbagi disitulah letak kemanusiaan yang tertinggi. Begitu juga Rasulullah pernah menjelaskan tentang keutamaan bersedekah di masa sulit:
“Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?” Beliau menjawab, “Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat disertai pelit (sulit mengeluarkan harta), saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, “Untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian, dan harta itu sudah menjadi hak si fulan.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 1419 dan Muslim no. 1032).
Perancis bukan Negara Islam tidak sedikit pula penduduknya yang tidak meyakini Tuhan, namun perancis masa kini telah menjadi negara yang bukan hanya menjujung Hak Asasi Manusia namun hak dan kesejahteraan Hewanpun mereka perjuangkan. Seharusnya umat Islam Indonesia yang mayoritas muslim dapat melakukan hal yang demikian karena nilai dan ajaran Islam adalah untuk memuliakan manusia dengan jalan saling tolong menolong, Rasulullah SAW telah menyampaikan hal ini dalam sabdanya:
“Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali setelah tahun ini aku tak bisa lagi berjumpa dengan kalian selama-lamanya. Wahai umat manusia, sesungguhnya darah kalian, harta dan harga diri kalian itu mulia, sebagaimana mulianya hari ini dan bulan ini. Kalian kelak akan bertemu Tuhan, dan Ia akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan yang kalian lakukan. Ingatlah, setelah aku wafat janganlah kalian kembali ke dalam kesesatan, di mana sebagian di antara kalian memukul atau membunuh sebagian yang lain.”
“Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, leluhur kalian juga satu. Kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada Non Arab atau ‘ajam, Non Arab tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih utama daripada yang berkulit putih, orang kulit putih tidak lebih utama dari yang berkulit merah kecuali (disebabkan) tingkat ketakwaannya.”
Nabi Ibrahim memberikan contoh atas dasar cinta kepada Allah yang melebihi segala-galanya, keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang terberkati. Nabi Ibrahim diberi gelar “khalîlullah” atau kekasih Allah, dan dari keluarga ini lahirlah keturunan-keturunan para nabi seperti Nabi Ishâq, Nabi Ya‘qûb, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.
Tentu sebagai Ummat yang beragama Kisah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam di atas mengajarkan kepada kita bahwa beragama adalah pengorbanan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Beragama adalah usaha menjadikan diri kita sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang tidak diperbudak oleh nafsu atau manusia lainnya, melainkan manusia yang menghamba dengan seutuhnya di hadapan Allah subhanahu wata’ala.
Semoga Spirit dan ajaran Bapak Para Nabi Ibrahim serta para nabi dan Rasul lainnya dapat memotivasi kita untuk saling tolong menolong sebagai wujud kepedulian bagi sesama, saling merigankan serta berdoa semoga pandemi yang sedang kita alami segera berakhir, kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, serta selalu berada di dalam lindungan Allah subhanahu wata’ala.