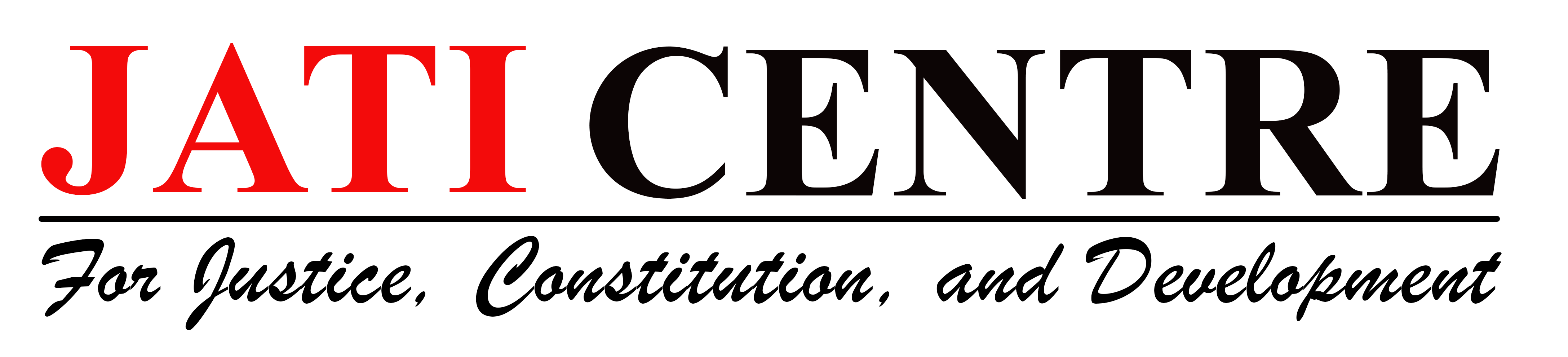Oleh : Saeful Ihsan (Penulis Buku dan Novel)
Kerumitan, adalah sesuatu yang selalu muncul saat kita mempelajari filsafat. Ada banyak kosa kata baru yang terbentuk dari proses berpikir. Berpikir sendiri adalah proses kontemplasi atas kosmos, kesadaran menangkap hal yang lebih dari apa yang telah dibahasakan sehari-hari. Kita ambil contoh kata “ada”. Sehari-hari kita jumpai derivasinya yaitu “berada”, “keadaan”, dan “keberadaan”.
Dalam lapangan filsafat, “ada” menghasilkan “mengada”, yaitu berproses menjadi ada. Dalam bahasa Arab “ada” adalah wujud, mengada berarti mewujud. Dalam filsafat Islam, kita sering mendengar kata maujud, yang juga sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti berwujud, atau nyata (lihat KBBI).
Apalagi saat mempelajari pemikiran Martin Heidegger, filsuf eksistensialis Jerman, sangat rumit untuk dipahami. F. Budi Hardiman dalam “Heidegger dan Mistik Keseharian”, menuturkan bahwa rumitnya mempelajari buku Heidegger “Sein Und Zeit” (ada dan waktu); Hanya sedikit sekali yang dapat memahami bukunya, demikian Heidegger, bahkan Jean Paul Sartre (filsuf eksistensialis yang lain) tidak termasuk di dalam yang sedikit sekali itu.
Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia, dimana tradisi pemikiran filsafat tidak membumi? Pasti lebih rumit lagi. Oleh sebab itulah F. Budi Hardiman mencoba mengintroduksi pemikiran Heidegger dari buku “Sein und Zeit” ke dalam buku “Heidegger dan Mistik Keseharian”. Berharap buku itu bisa menjadi jembatan menuju ke dunia pemikiran Heidegger yang sangat rumit itu.
Tetapi bagi saya, buku yang ditulis oleh Hardiman itu tetap saja terasa rumit. Utamanya karena permainan istilah-istilah dari Heidegger yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia: ada-mengada, waktu-mewaktu-kemewaktuan, ada-dalam-dunia, membuka diri pada ada-di sana (dasein), dll. Mungkin akan lebih mudah jika diantar dengan satu kisah hidup seseorang sebagai dasein.
*
Demi kemudahan, saya mengilustrasikan cerita ini:
Seorang karyawan bernama Andre–masih muda (sekira 22 tahun) belum menikah–duduk merenung di teras kantor tempatnya bekerja, pada jam istirahat. Teman lain lewat, katakanlah namanya Fajar, mengajaknya mengobrol dan melupakan segala urusan yang membuatnya selalu murung, diam, dan mengkhayal.
Andre pun menjadi riang, dia larut dalam obrolannya bersama Fajar. Mereka bercengkerama, bergurau, menjadikan pengalaman di kantor sehari-hari yang kadang mengesankan sebagai lelucon: ada sesekali kesialan yang menimpa. Misalnya kelalaian kerja yang membuat mereka harus mengganti rugi, atau membayar denda. Ataukah ada keisengan-keisengan kecil kepada teman-teman karyawan yang lain, yang begitu asyik untuk ditertawakan. Bukankah menertawakan kesialan merupakan salah satu kenikmatan dalam hidup?
Atau misalnya berangan-angan untuk membeli rumah atau mobil mewah, berandai-andai punya isteri cantik dan anak yang lucu-lucu. Mereka lalu membayangkan bagaimana jika sekiranya pihak kantor menaikkan gaji mereka berlipat-lipat, lalu mereka menabung, dan khayalan akan terwujud. Berhari-hari seperti itu.
Hingga suatu hari, Fajar mengetahui bahwa Andre, sahabatnya itu dilanda masalah yang rumit: pacarnya yang bernama Nia, berbeda agama dengannya, hamil akibat hubungan cinta mereka. Bersamaan dengan itu, Andre baru tahu bahwa pacarnya ini sesungguhnya adalah isteri dari seseorang yang telah pergi jauh, pulang ke orangtuanya, dan dipastikan tidak akan kembali.
Pertama-tama, Andre dihadapkan pada pilihan: meneruskan hubungan, ataukah meninggalkan perempuan yang menipunya itu? Jika memilih meneruskan, maka Andre harus menghadapi sejumlah kenyataan. Ia harus meminta izin kepada orangtuanya untuk menikahi perempuan yang berbeda agama dengannya itu. Ia juga harus berani menemui orangtua si wanita itu yang juga berbeda agama dengannya, dan dengan orang tuanya. Ia juga harus menerima kenyataan akan kelahiran anaknya, sekaligus rumitnya menyelesaikan urusan, termasuk dokumen-dokumen dari seorang isteri yang belum dijatuhi talak resmi dari suaminya.
Jika memilih meninggalkan perempuan itu, Andre berarti harus menerima dirinya sebagai seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab, dan anak yang akan ditinggalkannya, kelak akan dirindukannya.
Fajar jadi mengerti, mengapa sahabatnya itu menjadi perenung yang dalam, menyendiri di tepi kesibukan sehari-hari. Sebagai seorang teman, Fajar berupaya menghibur temannya itu, mengalihkannya dari kepusingan dengan pelbagai obrolan. Agar sahabatnya itu tetap kuat menghadapi kenyataan yang begitu pelik.
*
Kita bisa membuat pengandaian dengan cerita yang lebih mudah. Kisah yang rumit itu saya ajukan, berharap dapat dengan mudah untuk menggambarkan kumpulan peristilahan Heidegger yang banyak dan baru itu.
Dari kisah itu, Andre kita andaikan sebagai dasein (ada-di sana). Tiba-tiba saja Andre muncul sebagai seseorang (faktizitat) yang penuh masalah. Itu yang tampak bagi kesadaran kita yang membaca cerita ini, dan juga bagi sahabatnya–si Fajar. Bagi Andre sendiri, diapun tiba-tiba saja ada, tak tahu datang dari mana, mau ke mana, dan untuk apa dia hadir. Andre hadir sebagai dasein, hadir sebagai manusia yang memililiki kecemasan. Ia terlempar, jatuh dari kesehariannya sebagai manusia yang merenungi kehadirannya di muka bumi.
Bagaimana tidak, bayangan akan adanya suatu kenyataan yang mencemaskan–yakni kematian–menghantui dibalik peristiwa yang dibayangkan akan datang; keluarga si perempuan yang dihamilinya, pada kemungkinan terburuknya, akan membikin perhitungan. Juga rasa malu kepada keluarga sendiri. Serta kemungkinan ancaman yang akan datang dari pihak suami dari perempuan yang dihamilinya.
Semua yang ada, tampak bagi kesadaran Andre, membuatnya menjadi otentik; dasein yang merenungi kehadirannya di dunia ini. Ada yang lain–Nia, keluarga Nia, keluarga Andre sendiri, suami Nia, jabang bayi dalam perut Nia–menyebabkan Andre berupaya mengantisipasi kemungkinan terburuk dari masa depan. Di sinilah ada-nya Andre tidak final, Andre akan terus menerus atau selalu menjadi (werden) Andre hingga datang suatu titik sempurna ke-Andrean-nya, yaitu pada saat ia mati.
Jadi, jika kita menganggap kita yang otentik adalah “aku yang sekarang”, Heidegger justeru menganggap keotentikan itu adalah kemewaktuan, atau kemenjadian kita. Artinya, kita yang otentik adalah kita yang terus menerus berproses menjadi kita yang sempurna. Sebab kita masih terus berubah. Kita berkata “inilah saya” sekarang, akan beda dengan “inilah saya” pada masa-masa mendatang.
Kita tentu ingat Ahmad Wahib mengatakan “aku bukan Wahib”, maksudnya “aku me-Wahib… aku yang terus menerus berproses menjadi Wahib”. Wahib adalah Wahib pada saat ia sakaratul maut. Keberadaan Wahib di masa tertentu, tidak bisa disimpulkan bahwa itulah Wahib secara keseluruhan. Sebab, Wahib masih berurusan dengan masa depan. Di masa depan, Wahib akan menjadi Wahib yang lain dari yang sekarang. Wahib akan masuk ke dalam dunia yang berbeda, ada keseharian di sana, dan mungkin kontemplasi atau perenungan menjadikan dia Wahib yang berbeda dari yang seharusnya.
Salah satu konsep dasein, adalah ada-di dalam-dunia (in-der-welt-sein). Adanya Andre di dunia bukan seperti adanya mobil di dalam garasi, atau adanya buku di dalam lemari. Andre tidak diletakkan di dalam dunia, tetapi Andre menempati, memukimi dunia (wohnen).
Dunia yang dimaksud bukanlah bumi, tetapi ruang-ruang kehidupan yang ditempati. Makanya menurut Hardiman, istilah bahasa Indonesia “meninggal dunia”–bukan meninggal bumi–bagus sekali untuk menggambarkan dunia yang dimaksud. Saat Andre mati, ia masih di bumi (dikubur di tanah atau dikremasi), tapi tak ada lagi di dunia keseharian. Di sinilah menariknya: Andre, selanjutnya akan hidup di dalam dunia ingatan orang-orang yang mengenalnya.
Dasein memukimi dunia, di sana ada pekerjaan, ada hiburan, ada pertemanan, ada permainan, ada karir, ada liburan, dan lain sebagainya. Dunia yang di dalamnya terdapat kolam keseharian, dan kadang dasein tenggelam di dalamnya, sehingga lupa terhadap keotentikannya, ia lupa kalau ia berada di dunia begitu saja, ada untuk tiada–mati.
Saat Andre merenung, ia sadar akan kehadirannya di dunia. Segera saja Andre akan merancang suatu langkah antisipatif di masa depan. Karena proses mengada memang mengandung rancangan (entuwurf). Ia akan masuk ke dunia baru dan akan memulai sebagai ada yang selanjutnya; Andre akan menjadi bapak, namun sebelum itu, ia kemungkinan akan menghadapi caci maki, bahkan disakiti secara fisik oleh keluarga perempuan yang dihamilinya–sehingga ia cemas. Saat kecemasan itu benar-benar disadarinya, ia menjadi otentik sebagai dasein, manusia yang merasakan keterlemparan.
Fajar muncul atau berada sebagai orang lain yang tampak pada kesadaran Andre. Fajar juga memukimi dunianya, dunia yang sama dengan dasein atau manusia yang lain, tenggelam dengan urusan keseharian. Fajar muncul menghibur Andre, dan Andre tenggelam ke dalam keseharian, tenggelam ke dalam dunia bersama (mitwelt), dan melupakan keterlemparannya (geworfenheit). Terlibat percakapan (rede) bersama fajar adalah cara dia melupakan keterlemparan itu.
Bekerja di kantor, bisa jadi bukan hanya cara mengantisipasi masa depan, tetapi juga merupakan sebentuk tenggelam ke dalam kolam keseharian. Keseharian di sini bermakna rutinitas, kesibukan, atau aktifitas. Wajar saja, sebab apa yang ditangkap oleh manusia adalah sesuatu yang menampakkan diri.
Dari sini, nampak bahwa Heidegger sangat dipengaruhi oleh Edmund Husserl tentang intensionalitas (keterarahan “kesadaran” pada “sesuatu”). Akan tetapi, jika Husserl fokus pada kesadaran, Heidegger justeru fokus kepada “sesuatu”–ontologi dan ontiz (berkaitan dengan mengada).
Hardiman mengandaikan sebuah lapangan golf, di dalamnya ada tiga macam: pertama, lapangan, tongkat pemukul, bola, lubang, ini disebut dengan Zuhandenes (siap-untuk-tangan), sama dengan alat-alat pertukangan, ia ada untuk digunakan; kedua, pohon-pohon, tanah, dan bebatuan adalah Vorhandenes (tersedia-di depan-tangan), adalah benda-benda yang tersedia begitu saja, ia ada tak berhubungan dengan kita; ketiga, orang-orang yang bermain golf, adalah dasein yang lain, kita dengan mereka sama-sama dasein yang memukimi dunia disebut mitdasein (berada-di sana-bersama).
Menurut Heidegger, ketiga macam “ada” di atas memiliki cara berada atau menyingkapkan diri masing-masing: Zuhandenes menampilkan diri sebagai alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, mengerjakan sesuatu, kesibukan keseharian. Vorhandenes menampilkan diri sebagai benda yang tidak penting, tidak berhubungan dengan pekerjaan kita, ia sendiri tak berhubungan dengan kita. Mitdasein, keberadaan dasein atau manusia yang lain menampilkan diri memiliki hubungan dunia dengan kita, yaitu dunia-bersama (mitwelt).
Dasein memiliki cara menghadapi ketiga ada itu. Zuhandenes dan Vorhandenes, karena kehadirannya sebagai benda mati, cara menghadapinya adalah diurus atau ditangani (besorgen). Sementara mitdasein, karena berada-bersama (mitsein) dengan dasein, maka cara menghadapinya adalah dipelihara–pemeliharaan (fusorgen).
Tenggelam dalam keseharian adalah kelarutan dasein atas besorgen. Kesibukan dengan alat-alat, untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Adapun fusorgen melarutkan dasein dengan cara bercakap-cakap (rede), memahami (verstehen), menafsirkan. Fusorgen dimaksudkan dalam rangka ada bersama di dunia, dunianya adalah dunia bersama. Cara untuk dasein larut ke dalam fusorgen adalah berusaha melupakan keterlemparan, masuk ke dunia bersama agar dianggap ada, atau hadir (eksis).
Seseorang yang hanya memiliki sepeda motor merk Yamaha Mio, tidak bisa masuk ke dalam dunia klub motor merk Ninja RR. Si pemilik Mio mengalami keterlemparan, dia tidak dianggap berada dalam dunia Ninja RR. Dia bisa masuk ke dunia itu dengan meninggalkan keterlemparannya, dengan memfokuskan diri pada besorgen, yaitu berupaya membeli motor Ninja RR. Barulah ia dianggap berada dalam dunia itu. Cara mengada si pemilik Mio itu dengan melakukan fusorgen, memelihara hubungannya dengan dasein yang lain.
Percakapan, atau obrolan (rede), juga adalah cara dasein larut dalam keseharian. Fajar yang mengajak Andre bergurau dan melakukan kesibukan lain, agar melupakan masalahnya, itu adalah bentuk pelarian.
Lalu apa yang mendasari itu semua? Dan inilah kunci dari segala rahasia keberadaan manusia (dasein), adalah kematian. Kematian menjadi dasar seseorang hadir di muka bumi. Semua gerak manusia, apakah itu tenggelam dalam besorgen, maupun fusorgen, semuanya bergerak berdasarkan kesadaran akan kematian. Dasein sendiri ada untuk mati.
Maka menurut Heidegger, cara untuk mengatasi keterlemparan adalah dengan merenungi atau menghayati dengan intim kehadirannya sendiri. Mengapa Heidegger tidak mengarahkan dasein pada agama? Sebab agama juga adalah pelarian, ritual agama adalah keseharian yang lain. Nasihat agama memalingkan dasein dari kesadaran eksistensialnya, tujuannya.
Agama sering berkata, “Setiap manusia akan mati”. Dengan demikian, manusia tidak akan menghayati kematiannya. “Toh juga akan mati, kan?” Iya, setiap orang memang akan mati, tetapi mati adalah masalah individual, manusia harus menghadapinya sendiri. Setiap orang harus antisipatif terhadap kematiannya. Sementara kata “semua manusia akan mati” adalah sebentuk penghiburan supaya manusia lupa akan kenyataannya menghadapi kematian itu sendiri.
Jadi menurut Heidegger, sejak kemunculannya, manusia (dasein) sudah mengalami kejatuhan (Verfallenheit). Saat manusia hadir di dunia, dia sudah dilekati oleh kematian. Dasein tidak dapat merancang kematian, kematian sudah bersiap datang kapan saja. Dasein hanya melakukan antisipatif dengan menghayati kehadirannya, ataukah justeru lari dari kesadaran akan dekatnya kematian, yaitu dengan tenggelam dan larut dalam keseharian.
Inilah yang ditangkap oleh Hardiman sebagai “mistik keseharian” dari “Sein und Zeit” karya Heidegger itu. Mistik di sini bukan bermakna klenik, takhayul, atau mitos-mitos, tetapi suatu kebisajadian karena kedatangannya pasti–kematian.
Tetapi, Heidegger lebih radikal soal kematian ini. Manusia sebagai dasein (mengada) sesungguhnya sudah mati berkali-kali. Hal ini sekaligus memunculkan pandangan sebaliknya, yakni kelahiran. Hardiman dalam salah satu sub judul bukunya itu (Heidegger dan Mistik Keseharian), jadi bertanya; apakah mortalitas, atau natalitas, keabadian ataukah kelahiran?
Kelahiran yang dimaksud bukanlah secara biologis, tetapi dalam rangka Sein und Zeit, ada dan waktu, yakni dasein. Manusia itu telah mati dari dunia yang satu, dan terlahir lagi ke dunia yang lain. Kelahiran kembali itu adalah memulai lagi yang baru. Saat Andre dipecat dari kantor, pada saat itu dia telah mati dari dunianya. Pindahnya Andre ke dunia pekerjaan yang lain, ataukah masuk ke dunia pengangguran, berarti ia terlahir (memulai) kembali.
Namun Heidegger, tidak meyakini adanya sebuah kehidupan setelah mati–dalam arti mati yang sesungguhnya. Dasein hanya ada untuk dunia ini, tiada dunia kedua bagi dasein. Tetapi Heidegger memberi penghargaan kepada dasein dengan membuatnya hidup kembali di dunia ingatan orang-orang. Keluarga atau sahabat, atau siapa saja yang mengenal kita, tetap akan menyaksikan kita hidup dalam kenangan mereka saat kita sudah mati, yaitu apabila mereka menghadirkan kembali kenangan bersama kita–kira-kira seperti itulah mortalitas kita.
Hal itu memberi pengetahuan lagi bagi kita, bahwa sesungguhnya kita ini “terserak” (zerstreut)–kata Hardiman. Kita berada di mana saja. Hardiman berkata “pemudik itu, karena dengan memori itulah mereka menghadirkan ruang yang telah dimukimi itu kembali”. Maksudnya, fenomen kehadiran kita mengisi ruang-ruang kehidupan yang pernah kita mukimi. Kita pernah ada di masa lalu, pernah ada di kampung atau di kota, kita ada sekarang, dan nanti akan memukimi dunia ingatan orang-orang.
Pada bagian akhir bukunya, F. Budi Hardiman membahas soal waktu dan kemewaktuan. Mengutip Benjamin Franklin, “Time is money”, waktu adalah uang, betapa manusia modern ditaklukkan oleh waktu, padahal dia sesungguhnya bisa menaklukkan waktu. Manusia adalah waktu, dan kehadirannya adalah mewaktu, ia hidup dalam relung-relung kehidupan, dalam ceruk-ceruk waktu.
Hardiman juga menyundul relativitas Einstein, dalam segi waktu ke bagian akhir bukunya itu. Manusia bisa merasakan waktu objektif sekaligus waktu subjektif. Waktu objektif, atau yang di luar manusia adalah waktu normal (1 jam = 60 menit). Sementata waktu subjektif, yang ada dalam diri, bisa lebih lama atau lebih cepat dari waktu yang normal (1 jam menunggu, dengan 1 jam ditunggu, lamanya tidak sama), tergantung dari suasana hati.
Time is money menaklukkan manusia menjadi tenggelam dalam besorgen (larut dalam keseharian). Hal ini, punya analogi dalam Alquran surat al-Ashr ayat 1-2: “Demi masa (waktu), sesungguhnya manusia berada dalam kerugian”. Manusia seperti itu, ditaklukkan waktu, sebab mengejar suatu produktifitas yang melupakan pentingnya mitdasein (kehadiran orang lain), dan juga melupakan makna kehadirannya sebagai dasein yang senantiasa diintip oleh kematian.
*
Sayyidina Ali mengatakan, “Orang yang paling cerdas adalah yang mengingat kematian”. Kalau begitu, Heidegger termasuk diantaranya. Hanya saja, sayang sekali ia tidak menemukan dirinya dalam agama. Ia memahami adanya-agama berdasarkan apa yang tampak dalam kesadarannya, praktik agama yang ia saksikan di lingkungannya.
Heidegger berhenti pada dunia, dan tidak bisa menjangkau apa yang terjadi setelah mati. Akhirnya, dasein dilarikan ke dalam kesadaran. Di sini, tampaknya Heidegger terpaksa harus membuat dasein bermakna ganda; di satu sisi dasein adalah manusia dalam wujud yang asli, di sisi lain dasein adalah manusia berwujud kenangan.
Sementara, hanya agamalah yang punya informasi tentang kehidupan sesudah mati, tentu melalui kitab suci sebagai sumber ajarannya. Agama sendiri, agar bisa diyakini, setidaknya perlu dibuktikan kebenarannya. Untuk yang terakhir ini, agama sesungguhnya sudah mengantisipasi dirinya bakal dipertanyakan di kemudian hari (di jaman modern ini), maka kitab suci menciptakan sebuah pelindung yang bernama “isyarat ilmiah”. Untuk Alquran disebut “I’jazul Quran”, kemukjizatan Alquran.
Heidegger juga tidak menemukan dasein berasal dari mana. Tiba-tiba saja muncul dalam kejatuhannya seperti itu. Jikapun ia akan berkata, bahwa “kemendahuluan dasein bagi dunia, sama dengan kememdahuluan makna atas penyampaian makna”, tetapi tetap saja, ketiadaan sistem penjelas bagi awal kemunculan dasein menandakan ada yang hilang (missing link) pada sistematika “Sein und Zeit” nya.
Sementara yang missing dalam pemikiran Heidegger itu dijawab hampir mendetail oleh agama–jika bukan karena garis-garis besarnya saja, yakni dalam kitab suci.
Akan tetapi, ada persamaan pandangan antara Heidegger dan agama-agama, yakni mendasarkan hidup pada mati. Mati adalah alasan mengapa manusia mengada di dalam dunianya.