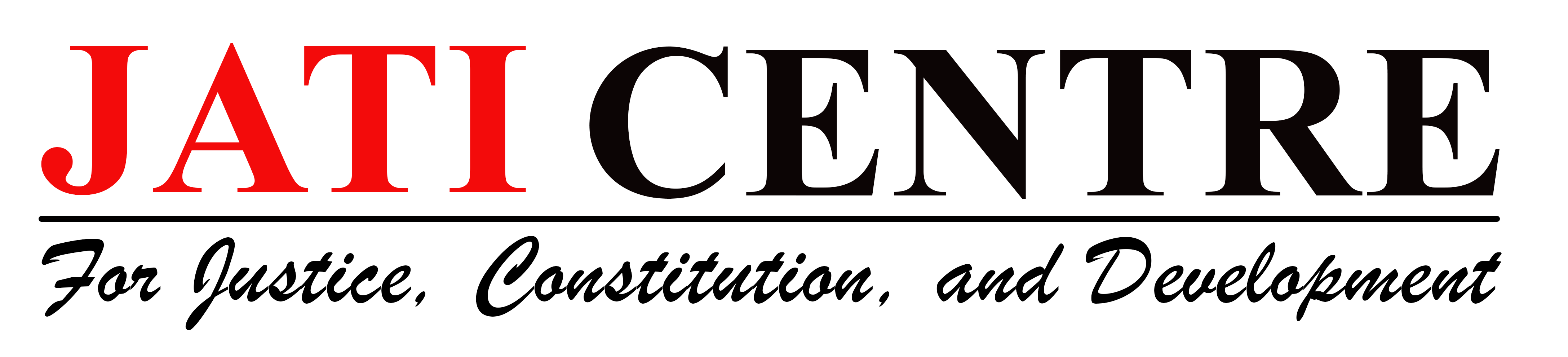Demokrasi Tidak Akan Benar-Benar Mati

Demokrasi Tidak Akan Benar-Benar Mati
Oleh : Saeful Ihsan, S.Pd., M.Pd.
(Penulis Muda Sulteng)
Ketika Anies Baswedan menampilkan fotonya memegang buku bersampul hitam, “How Democracies Die”, dan dimaksudkan sebagai sebuah pernyataan sikap: Indonesia menghadapi ancaman kematian demokrasi. Lalu, itu lebih tepatnya ditujukan kepada siapa?
Kepada pemerintah (pusat) kah? Yang selama ini terkesan antikritik, tidak mendengar suara rakyat, lalu berupaya membatasi kebebasan? Ataukah pihak yang aktif mengkritik pemerintah? Utamanya, PA 212 atau para simpatisan Habib Rizieq Shihab (HRS), serta FPI. Di mana, mereka kerapkali dinilai melakukan aksi-aksi yang mengguncang demokrasi.
Dari sudut pandang kita sebagai penonton, sudah pasti yang dituju adalah yang pertama disebutkan. Soalnya Anies terlihat lebih dekat kepada kelompok yang disebut “Umat Islam” itu. Sebaliknya, terkesan berhadap-hadapan dengan pihak pemerintah pusat, salah satu bentuknya, kebijakan lokal DKI sering tidak mendapat respek dari pusat.
Matinya demokrasi menurut buku yang dipegang Anies itu “How Democracies Die” karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, didasarkan pada empat indikator:
“1) rejects, in words or action, the democratic rules of the game, 2) denies the legitimacy of opponents, 3) tolerates or encourages violence, or 4) indicates a willingness to curtail the civil liberties of opponents, including the media.” (Levitsky and Ziblatt, 2018: 18)
Indikator itu sendiri adalah pengembangan dari karya Juan Linz, ‘The Breakdown of Democratic Regimes’, tentang tokoh otoriter, yang kalau mereka berkuasa, cenderung akan mematikan demokrasi. Hal itu dibuktikan oleh sejarah terjadi pada Italia dengan berdirinya rezim fasis Benito Mussolini; Adolf Hitler di Jerman; Hugo Chavez di Venezuela, dan beberapa lainnya.
Mereka, para tokoh otoriter itu memang naik ke tampuk kekuasaan bukan dengan jalan kudeta militer–meski sebagiannya mencoba jalan kudeta di awal hingga akhirnya memilih jalan konstitusional setelah percobaannya gagal, dan setelah mereka berkuasa, cenderung melakukan keempat indikator di atas.
Untuk konteks Indonesia saat ini, setidaknya rezim cenderung menggunakan cara keempat–membatasi kebebasan lawan, dan pers. Walau tidak begitu keras. Rezim menjadikan Anies sebagai lawan, dan kelihatan berupaya membatasi pergerakannya lewat apresiasi yang minim terhadap program pemprov DKI. Juga narasi-narasi miring yang diembuskan oleh para simpatisan istana.
Juga bagaimana istana memandang HRS beserta simpatisannya sebagai lawan. Terlihat dari bagaimana istana menyoroti kumpul-kumpul di bandara dalam penyambutan HRS. Sementara pilkada di Solo yang juga kumpul-kumpul tak disoal. Padahal, kata kunci dari pencegahan penularan wabah korona adalah ‘jangan berkumpul!’
Namun, jika kita mengikuti logika buku “How Democracies Die”, yang berpeluang untuk menjadi tokoh otoriter dan mematikan demokrasi adalah HRS beserta kroni-kroninya. Secara, HRS adalah tokoh populer, tetapi seruan-seruannya juga lebih kepada memilih jalan kekerasan untuk menegakkan keadilan.
Juga bagaimana cara HRS merespons kritikan arau protes terhadap dirinya. Frase ‘Lonte’ dalam ceramah di maulid nabi beberapa waktu lalu, membuat kita bisa berkesimpulan singkat, bahwa HRS akan bersikap frontal terhadap lawan-lawannya, seandainya saja kekuasaan itu sudah dipegangi.
Sejak tahun 2016, HRS sudah mengampanyekan konsep NKRI Bersyariah. Ide itu direspons oleh Denny JA dengan narasi tandingan, ‘NKRI Bersyariah, atau Ruang Publik yang Manusiawi?’ Denny JA menuliskannya dalam sebuah esai. Lalu tulisan itu ditanggapi oleh 16 orang (yang dinilai sebagai) pakar–salah seorang di antaranya adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra–menjadi sebuah buku.
Buku itu memang tidak menyinggung demokratis atau tidaknya, tetapi bagi Denny JA, ruang publik manusiawi itu sudah sesuai dengan Islam, tak perlu NKRI Bersyariah. Agaknya, penggunaan istilah Bersyariah kurang demokratis, sebab syariah selalu dimaknai dengan rigid, berdasarkan tafsir yang tekstual.
Lagipula menurut Denny JA, indikator NKRI Bersyariah harus jelas. Kalau standar keadilan dan ketentraman suatu negara mengambil indikator sesuai Alquran dan Sunnah, negara-negara paling mempraktikkan standar-standar Islami menurut survei justru adalah negara-negara yang di dalamnya sedikit umat islamnya: Selandia Baru, Belanda, Swedia, Irlandia, Swiss, Denmark, Kanada, dan Australia.
Tetapi memang wajar, jika ada tawaran sistem lain untuk suatu negara. Termasuk di Indonesia. Soalnya, Dr. Satrio Arismunandar dalam memberikan pengantar buku kompilasi 16 pakar menanggapi Denny JA, menampilkan data tingkat pro-Pancasila, yang berarti juga pro demokrasi–soalnya Pancasilais berarti juga demokratis, dari tahun ke tahun terus menurun. Dalam kurun 13 tahun, pro-Pancasila turun 10%.
Penurunan tersebut disebabkan oleh tiga hal: kesenjangan ekonomi, paham alternatif,
dan sosialisasi. Jadi, kegagalan-kegagalan yang terdapat dalam praktik pemerintahan sangat berpengaruh terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap (demokrasi) Pancasila, dan akhirnya mencari alternaif yang dianggap lebih bisa memperbaiki nasib bangsa daripada sistem demokrasi itu sendiri.
Namun, betapapun misalnya rezim saat ini dianggap mewarisi watak otoriter Orde Baru, ataukah HRS dianggap sebagai tokoh demagog, demokrasi hanya akan menurun menjadi kurang demokratis, tidak sepenuhnya akan mati. Dari beberapa indikator negara demokrasi Abraham Lincoln dalam pidatonya di Pettysburg tahun 1863, “peran media yang bebas” sebagai aktualisasi kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat menjadi, dominan dalam tafsiran kita.
Sementara, manusia secara individual adalah satu-satunya makhluk yang dianugerahkan demokrasi di dalam kepalanya. Yaitu, bebas berpikir, memilih jalan, dan menentukan nasibnya sendiri. Anugerah itu tidak akan benar-benar hilang, tetapi bisa dibatasi, sampai tak terbatas, oleh pemerintahan yang berusaha membunuh demokrasi, lewat watak otoritariannya.
____
Referensi:
Levitsky, Steven & Daniel Ziblatt. 2018. “How Democracies Die”, New York: Crown Publishing. Edisi bahasa Indonesia, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. 2019. “Bagaimana Demokrasi Mati”, Alih Bahasa oleh Zia Anshor, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Arismunandar, Satrio (Ed.). 2019. “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi, Cerah Budaya Indonesia