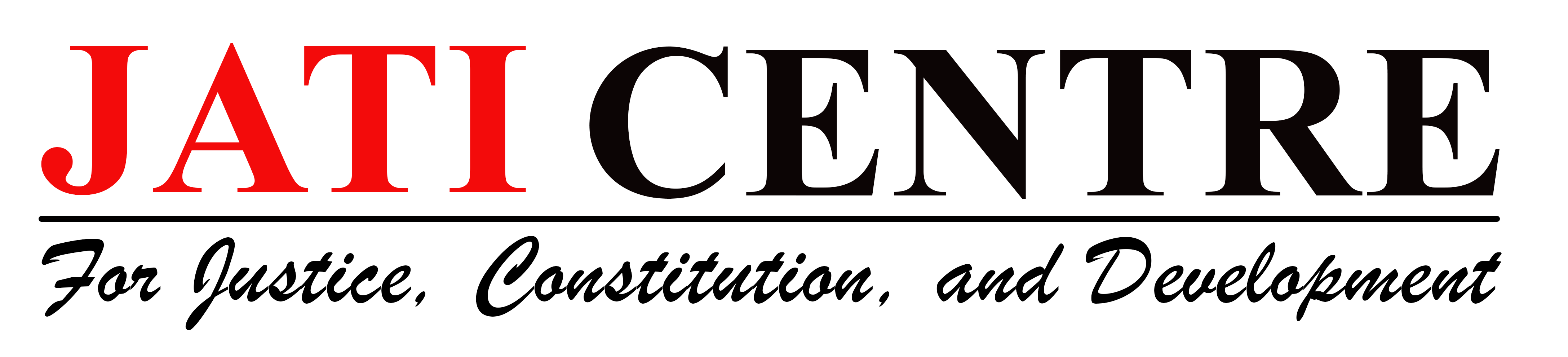MATINYA DEMOKRASI
Oleh : Ruslan Husen, SH., MH.[1]
Demokrasi, kata yang sering disebut dan didengar, terutama dari kalangan birokrat pemerintahan, pegiat pemilu dan penyelenggara pemilu. Demokrasi sebagaimana dicetuskan Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, mencitakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi saat ini menjadi sistem politik yang paling baik di dunia, walaupun sistem ini tidak menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sebab banyak juga negara otoriter yang tidak menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, malah lebih sejahtera. Tetapi, demokrasi dapat mengarahkan negara mencapai kesejehteraan dengan peran serta rakyat di dalamnya. Demokrasi menurut Syamsuddin Haris, sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik setiap masyarakat yang menyebut diri modern, sehingga pemerintah di manapun termasuk rezim-rezim totaliter, berusaha menyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke arah sistem politik demokratis itu.[2]
Demokrasi dikenali lewat wujud konstitusional penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin terbaik dari semua calon pemimpin yang berkompetisi pada periode tertentu. Selanjutnya pemilu dilaksanakan menurut aturan hukum dan aturan proses yang berpijak pada prinsip rechstaat atau rule of law. Aturan dimaksud sejatinya ditaati dan dilaksanakan semua stakeholders pemilu. Saat ketentuan pemilu ditaati dan dilaksanakan secara jujur dan adil, dikatakanlah pemilu-demokratis. Namun pemilu yang terlaksana minim integritas dan profesionalitas, banyak pelanggaran pemilu terjadi tanpa penyelesaian memadai maka pemilu akan kehilangan legitimasi publik yang pada akhirnya menggerus legalitas hasil pemilu.
Fenomena lain dari demokrasi yang hampir terjadi di semua negara dunia, yakni berubahnya wajah demokrasi dari demokrasi nyata menjadi “demokrasi selebritis”. Demokrasi selebritis berwujud bentuk “pencitraan diri”, yang mengandalkan polesan media massa dan penggunaan uang yang banyak untuk mencapai tujuan-tujuan politik tanpa perlu menekankan kepada substansi demokrasi. Menurut Munir Fuady dengan sistem politik selebritis atau pencitraan diri ini, akan tercipta sistem pemilu yang tidak berbasis pada kompetensi, melainkan pemilihan yang berbasis pada tingkat popularitas dan penggunaan uang melimpah guna membangun citra positif di tengah masyarakat. Mereka yang tampan, cantik, terkenal dan/atau banyak uang yang akhirnya akan dipercaya untuk menjadi pemimpin meskipun secara kualitas mereka diragukan.[3]
Sejatinya demokrasi hanya dapat dijalankan oleh para pemimpin negara yang amanah. Label amanah terlihat dan dirasakan oleh rakyat dari sikap, tindakan dan kebijakan pengelolaan negara. Sebab seorang pemimpin politik yang picik, akan menganggap musuh orang-orang yang kritis yang kebetulan berseberangan pendapat dengannya. Lebih fatal lagi, musuh tadi harus dikuasai kalau perlu dimusnahkan dengan berbahai cara, kendati dengan cara membunuh (menghilangkan nyawa), menculik atau membunuh karakter musuh. Tindakan irrasional dalam sudut demokrasi, seperti itu bisa saja terjadi, apalagi dikuasainya mayoritas struktur lembaga-lembaga negara dan kekuatan civil society potensial.
Ancaman Matinya Demokrasi
Demokrasi terlaksana melalui medium pemilu untuk periode masa jabatan tertentu, dengan melahirkan aktor pemimpin terpilih, baik dari kamar kekuasaan eksekutif (presiden dan kepala daerah) maupun dari kamar kekuasaan legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Pelaksana kekuasaan eksekutif dan legislatif menjadi satu kesatuan unsur pemerintahan hasil pilihan rakyat pemilik kedaulatan dalam suatu kontestasi pemilu. Terpatri asa, cita dan harapan kepada aktor pemimpin yang baru saja terpilih, agar mereka berani tampil dan berjuang memperbaiki tatanan sosial dan mengatasi keterpurukan sosial. Minimal realisasi janji-janji politik yang sering disampaikan kepada pemilih saat tahapan kampanye pemilu.
Namun ada kalanya aktor pemimpin pilihan rakyat berbalik menjadi masalah bagi rakyat banyak, miris saat aspirasi tidak lagi didengar dan diperjuangkan. Tindakan citra diri bisa saja atas nama rakyat tapi hakikatnya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara dan bertindak semata-mata mencapai keuntungan golongan dan pribadi semata. Pada posisi inilah titik krusial demokrasi yang melahirkan aktor pemimpin hasil pemilu, yang malah berbalik mempreteli prinsip-prinsip demokrasi, menjadi pemimpin diktator-otoriter. Demokrasi sejatinya menjadi solusi keterpurukan masalah sosial, malah melahirkan pemimpin anti kritik, mengkriminalisasi lawan politik, membatasi gerak kebebasan berpendapat, dan memperalat aparat penegak hukum untuk kelanggengan kekuasaan dengan kriminalisasi lawan-lawan politik.
Pada keadaan ini, demokrasi yang diagungkan dibajak beberapa kalangan elit politik, tentunya untuk kepentingan pribadi. Hakikat suara rakyat hasil pemilu berkembang untuk melindungi dan mencapai tujuan elit politik. Inilah yang dikhawatirkan dari pemimpin hasil pemilu bertransformasi menjadi pemimpin otoriter. Demokrasi perlahan-lahan mati dan dikalahkan oleh sistem pemerintahan yang dibangun dengan mengarah ke ciri diktator. Padahal pemimpin tersebut lahir dari proses demokratisasi. Steven Levistsky dan Daniel Ziblatt profesor Universitas Harvard Amerika, dalam bukunya “Bagaimana Demokrasi Mati (How Democracies Die), menyebut empat ciri-ciri kunci yang menunjukkan bahwa demokrasi telah berubah menjadi sistem pemerintahan berprilaku otoriter. Pertama, komitemen lemah atas aturan hukum. Kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Ketiga, intoleransi atau anjuran kekerasan. Keempat, membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media.[4] Matinya demokrasi ditandai dari keadaan-peristiwa kehidupan bernegara, yang erat kaitan dengan tindakan pemilik kekuasaan (pemerintah) mencerabut nilai dan prinsip demokrasi.
Pemerintah ciri diktator ini bisa saja lahir lewat proses pemilu, di mana tokoh politik menghimpun dukungan dengan menggunakan isu-isu populer dan argumen yang penuh prasangka terhadap lawan-lawan politik. Lalu terpilih dan naik ke puncak kekuasaan lewat proses pemilu, saat itulah Ia mulai menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan langkah menghancurkan lembaga-lembaga politik yang demokratis. Berupa lembaga politik dijadikan senjata politik untuk mengendalikan dan menghantam mereka yang berseberangan secara politik. Membeli media dan sektor swasta agar diam atau memihak kepadanya, serta mengubah aturan politik agar keseimbangan politik berubah menjadi merugikan lawan. Jadi inilah paradoks gawat yang harus dihadapi oleh sistem demokrasi.
Banyak upaya pemerintah berkuasa membajak demokrasi sehingga tampak “legal” dengan persetujuan lembaga legislatif dan diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi desain pencitraan, melalui upaya-upaya perbaikan demokrasi dengan membuat pengadilan lebih efesien, memerangi kejahatan dan korupsi, atau mendorong pemilu jujur dan adil. Media massa terbit setiap saat, tapi sudah dibeli atau ditekan pihak pemerintah sehingga menyensor diri sendiri. Rakyat terus mengkritik pemerintah tapi lantas menghadapi kriminalisasi. Jadilah masyarakat sebagian besar memilih jalan aman yakni apatis.
Pemerintahan dijalankan dalam sebuah skenario besar mempertahankan kekuasaan. Kritikan-kritikan berpotensi mengancam eksistensi kekuasaan lantas ditekan, dikriminalisasi dan diberangus dengan terlebih dahulu diajak masuk dalam lingkaran kekuasaan saling menguntungkan. Struktur kekuasaan lembaga negara dikuasai dengan cara mempergunakan otoritas mengisi dengan orang-orang loyal terhadap elit pemerintah. Pada sisi lain, jargon dan branding tentang pemerintahan demokratis, penegakan hukum dan perlindungan HAM terus disampaikan. Walau senyatanya berbeda, antara disampaikan dengan yang dilakukan pemerintah.
Ketahanan Demokrasi
Demokrasi sejatinya mampu mencari solusi untuk mendapatkan kebenaran relatif dan selalu dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Jadi demokrasi berhadapan dengan realitas perubahan yang abadi. Maka solusi yang diambil demokrasi tidak selamanya berwajah lembut, tetapi sering berwajah sangar dan berwatak radikal. Demikian pula demokrasi yang tampil dengan sangar dan radikal, juga dapat dirubah menuju demokrasi berwajah humanis dengan menghargai dan menegakkan hak asasi manusia.
Solusi demokrasi yang secara terus-menerus diperbaharui, mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat mestinya berwajah humanis, meskipun tidak harus berwajah lembut. Artinya, demokrasi responsif menyerap aspirasi masyarakat menurut ukuran terminologi sosiologis, yang sudah terpatri dan diterima dalam hati sanubari rakyat. Itu pun dengan membuang jauh-jauh watak absolut dari nilai-nilai tersebut, dengan tetap melindungi golongan minoritas, yang mungkin mempunyai pola pikir dan pola hidup berbeda bahkan berlawanan.
Demokrasi harus selalu mencari solusi terhadap masalah rakyat, serumit apa pun masalah tersebut. Padangan ini sejalan dengan ikhtisar International IDEA bahwa demokrasi harus bisa menawarkan solusi bagi pengelolaan konflik tanpa kekerasan yang dapat merekonsiliasi perpecahan dan perselisihan di dalam masyarakat serta membentuk dasar bagi perdamaian berkelanjutan.[5] Karena itu, demokrasi harus dapat menemukan berbagai macam kompromi di antara pihak yang berseberangan. Walaupun para pihak itu, memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan rakyat. Membiarkan suatu masalah rakyat tanpa solusi, akan bertentangan dengan sifat yang paling hakiki dari demokrasi. Dalam negara demokrasi, rakyat punya hak bahkan punya kekuatan.
Pertama, partisipasi masyarakat sipil. Keterlibatan warga negara dalam kerangka masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi ketahanan demokrasi. Adanya partisipasi masyarakat sipil turut menjadi kekuatan penyeimbang menjaga keutuhan demokrasi di tengah politik citra diri pemerintahan. Masyarakat sipil yang kuat membantu menciptakan kepercayaan mendasar bagi kelangsungan pemerintahan demokratis, melalui kritik konstruktif menguji kebijakan dasar. Jika komitmen masyarakat sipil terhadap tumbuh-kembangnya demokrasi, diikuti kontribusi menjaga gagasan ideal dan esensial demokrasi itu, kendati mendapat tekanan terorganisir dari pemerintahan otoriter, pada hakikatnya di sanalah kekuatan dan ketahanan demokrasi.
Kedua, kemandirian lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan sesuai konsensus kodifikasi peraturan perundang-undangan. Ciri khas demokrasi, menempatkan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Secara teknis, kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu tangan atau badan saja. Metode ini dilakukan agar tercipta kekuatan saling kontrol dan mengimbangi antar masing-masing orang, badan atau lembaga negara. Dengan metode ini, penyalahgunaan kekuasaan melanggar hukum dan hak asasi manusia dapat diperkecil. Apalagi dengan dukungan dan kolaborasi masyarakat sipil dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dalam bingkai rechstaat atau rule of law.
Ketiga, penegakan hukum yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Kekuasaan yudisial dalam proses penegakan hukum tidak tunduk terhadap kepentingan sektoral penguasa dan pengusaha. Penegakan hukum diarahkan pada pencapaian keadilan dan kebahagiaan umat manusia dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum. Hukum ditegakkan oleh struktur penegak hukum berintegritas dan profesional kendati berhadapan dengan kepentingan pragmatis kekuasaan dan pengusaha. Struktur penegak hukum yang menjalan fungsi badan yudisial dapat saja silih-berganti, akan tetapi semangat dan komitmen luhur penegakan hukum sejatinya membudaya dan terpatri kuat dalam sanubari aparat hukum.
Keempat, profesionalitas media massa menyatakan pendapat. Media merupakan pilar demokrasi penyambung aspirasi dan kepentingan mendesak publik. Mencapai pemerintahan demokratis, ditentukan peran media massa dalam menyampaikan secara kontinyu pesan dan harapan kepada masyarakat sebagai upaya pemulihan krisis dan mengatasi keterpurukan sosial. Media harus berani menyampaikan fakta dan opini kepada pemerintah terutama yang berpengaruh terhadap aspek tatanan kehidupan sosial politik dan tidak terjebak dalam keberlanjutan politik identitas aktor pemimpin.
Penutup
Praktik kehidupan demokratis sering kali mengecoh, format politik kelihatannya demokratis tetapi dalam praktik ternyata berwujud otoriter. Terjadi ketimpangan dan ketidaksesuaian antara demokrasi normatif (das sollen) dengan demokrasi empirik (das sein). Keadaan ini membuat demokrasi selalu hangat dikaji, apalagi dalam desain aspek tujuan kehidupan bernegara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Tampilnya aktor pemimpin dalam periode tertentu yang dihasilkan lewat proses pemilu demokratis adalah cita-harapan rakyat pemilih. Namun sangat disayangkan, belakangan hari berbalik menjadi pemimpin otoriter dengan mencerabut prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Ini menjadi luka trauma bagi demokrasi sebagai sistem politik yang diagungkan. Mengapa tidak, prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat menjadi dibatasi. Lembaga negara menjadi pelayan kekuasaan otoriter yang minim respon atas masalah sosial dan struktur pejabat lebih cenderung terus mempertahankan kekuasaannya. Penegakan hukum menjadi kehilangan arah idealitas, sangat tajam dan kuat ketika berhadapan dengan pelaku yang merupakan pihak dan pendukung dari lawan politik pemerintah. Bahkan aturan hukum (substansi) banyak diubah untuk kepentingan pemerintah dan merugikan pihak lawan politik.
Transformasi aktor pemimpin otoriter telah menjadi objek kajian di banyak negara, yang di satu sisi menumbuhkan semangat mempertahankan demokrasi. Pada sisi lain, menjadi kekuatan kritik kepada aktor pemimpin agar segera merefleksi diri akan tingkah membunuh demokrasi segera diakhiri dan penting menyadari kekuatan kedaulatan rakyat. Suatu saat rakyat akan bangkit menunjukkan kekuatan berdaulatnya, di tengah keterpurukan sosial yang terus menggejala dan menghantarkan aktor pemimpin otoriter pembunuh prinsip demokrasi ke gerbang kehinaan zaman.
Catatan Kaki:
[1] Penulis adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2022.
[2] Syamsuddin Haris dalam Topo Santoso dan Ida Budhiarti, 2019, Pemilu Di Indonesia; Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10-11.
[3] Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 26.
[4] Steven Levistsky dan Daniel Ziblatt, 2018, Bagaimana Demokrasi Mati (How Democracies Die), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 11-12.
[5] International IDEA, 2017, Mengkaji Ketahanan Demokrasi, International IDEA dan Perludem, Jakarta, hlm. 10.
Materi pdf : Matinya Demokrasi